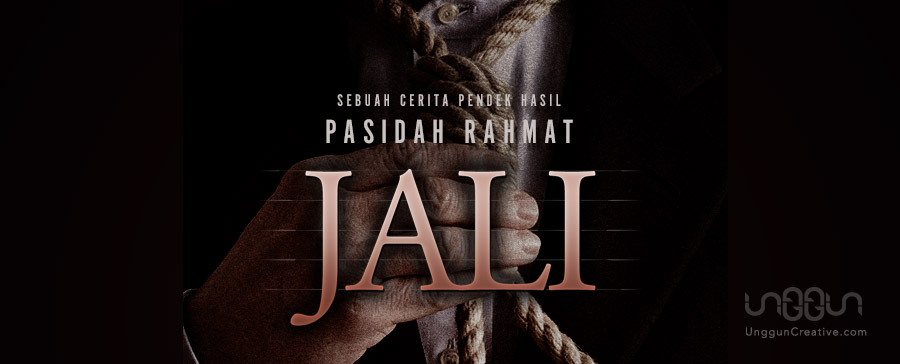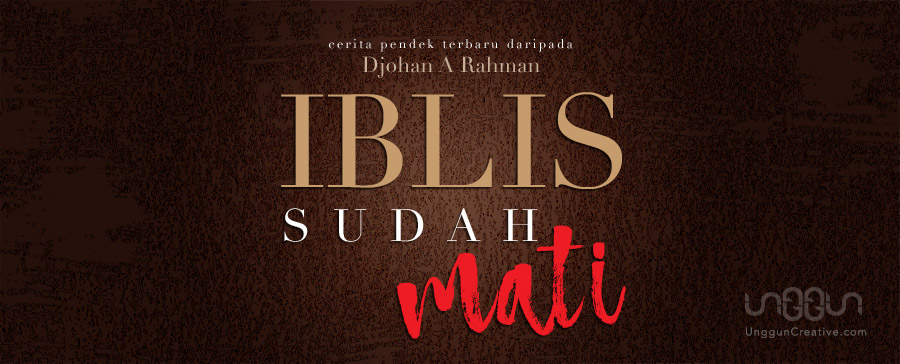Selat Sekerat

Malam hilang sepi. Air hilang tenang. Ketenteraman warga lubuk Sekerat Sini berkocak diusik gelodak perasaan si Jahan. Jahan ligat melawan arus di tengah-tengah malam yang masih tercengang-cengang dengan tindak-tanduknya yang tidak keruan. Dari celah-celah batu, melintas palang-palang besi, menembusi jeriji-jeriji bakau. Dari muka air, merempuh arus deras, menjunam hingga ke usus-usus selat. Setiap ceruk lubuk disergahnya. Setiap warga lubuk digegarnya. Jahan mahu semua warga lubuk meninggalkan tempat itu.
“Kita mesti lari. Lari jauh. Bawa semua anak-anak! Ajak semua kaum kerabat! Semuanya sekali! Satu pun jangan tinggal! Khabarkan kepada semua warga lubuk. Semua mesti tinggalkan tempat ini secepat mungkin!”
“Kenapa?”
“Sekarang!!! Sebaik-baiknya sekarang!!!”
“Kenapa?”
“Sekaraaaang!!!!!”
Air terus berkocak. Malam terus berombak. Namun tak satu langkah pun yang mula diorak. Jahan masih berlumba dari celah-celah batu, melintas palang-palang besi, menembusi jeriji-jeriji bakau. Dari muka air, merempuh arus deras, menjunam hingga ke usus-usus selat. Namun setiap warga lubuk yang mula berhimpun di situ hanya sekadar mengekori susup-sasapnya dengan bola-bola mata yang masih cuba memahami kemelut itu.
“Jangan jadi bodoh! Dengar cakap aku! Batu melintang tu! Mereka nak bongkar batu melintang tu!”
“Batu melintang tu?” terdengar suara separuh percaya. Bola-bola mata saling berpandangan. Semakin banyak warga lubuk berkumpul di sekeliling Jahan seolah-olah ada perhimpunan agung di lubuk Sekerat Sini.
“Mereka nak bongkar batu melintang itu?” Kepala Timah tiba-tiba terjengul dari celah batu. Matanya nampak berkaca, bersinar gembira. Sengeh di bibirnya jelas menandakan rasa senangnya. “Baguslah… ”
Jahan hairan melihat Timah menggelitis kesukaan. Jahan hairan Timah tidak melihat apa yang dilihatnya.
“Batu tu nak dibongkar?” suara Jebong bergema dari dalam tong dram yang sudah sekian lama menjadi kubunya “Betul? Betul mereka nak bongkar?” ulangnya lagi. Ketawa-ketawa kecil Jebong disambut dengan kedip-kedipan bebola mata yang masih termangu-mangu. “Dapatlah kita bertemu semula dengan warga Sekerat Sana… dengan saudara-saudara kita!”
Semakin banyak kepala-kepala terpantul dari celah batu, dari balik rumpai, dari belakang tong dram dan dari balik sauh karat tempat yu bodoh mengeram lesu. Terdengar bisik-bisik suara semakin gemuruh. Pandangan warga lubuk Sekerat Sini melekat pada kehitaman di dalam tong dram Jebong. Namun si tuan empunya suara masih diam di dalam kubunya. Hanya ketawa-ketawa kecilnya yang kedengaran.
“Kenapa kita mesti lari? Kalau mereka bongkar batu melintang itu, Sekerat Sini dan Sekerat Sana akan bersatu kembali!” Malong menyelit keluar dari beberapa rumpun rumpai yang lebat. “Aku pun dah bosan hidup di selat tersekat ini. Aku akan tunggu di sini! Aku mahu jadi yang pertama sekali menyeberang ke Sekerat Sana apabila terlihat kelibat laluan.”
Kata-kata Malong menggelegakkan lagi semangat yang lain. Lubuk kembali kecoh. Kepala-kepala kecil, leper, lebar, semuanya terhangguk-hangguk. Ternyata kata-kata Malonglah yang paling sedap diiyakan pada ketika itu. Tiba-tiba saja warga lubuk Sekerat Sini dijulang kesukaan, riang dilambung megah. Semangat mereka dibakar hingga meluap-luap. Mereka nekad mahu bersama Malong. Mereka juga mahu meluru ke Sekerat Sana bersama-sama Malong.
“Ya! Inilah masanya kita bertemu saudara-saudara kita yang telah lama terpisah!” Timah masih menggelitis kesukaan. Gembiranya bukan kepalang apabila Jebong dan Malong turut menyokong. Ketawa-ketawa kecil Jebong semakin galak kedengaran.
“Inilah masanya aku balik ke lubuk asalku,” sorak Togok sambil meluncur lalu bersama arus. “Dah cukup lama batu jahanam itu memisahkan kami! Baguslah kalau mereka nak bongkar! Batu jahanam tu pun memang tidak sepatutnya ada di situ! Kononnya mereka nak satukan Tanah Kecil dan Tanah Besar. Mereka bersatu, kita terpisah!”
Jahan semakin gelisah. Kata-kata Togok, Malong, Timah dan Jebong semakin menyukarkan usahanya. Jahan sudah mula hilang perhatian yang lain. Mereka dah termakan kata-kata Togok. Mereka dah telan bulat-bulat sorak-sorai Malong. Mereka dah terpukau senyum meleret Timah dan Jebong.
“Kita akan mati kalau kita tidak tinggalkan lubuk ini!”
Keadaan kembali kecoh. Terdengar keluh-kesah berhempas-hempas di sana-sini. Terbeliak-beliak bola-bola mata yang berhimpun di lubuk itu. Semuanya takut mati. Sekawan belanak terkebil-kebil kebingungan. Mereka masih tidak faham maksud Jahan. Warga lubuk lebih senang dengan kata-kata Togok, Jebong, Timah dan Malong. Hujah-hujah mereka halwa telinga yang lebih mudah dihadam. Lebih sedap ditelan. Lebih mudah difahami. Lebih senang dituruti… Tak payah bersusah-susah. Tunggu sahaja batu itu dibongkar. Tunggu sahaja laluan terbuka… Sudah. Mudah.
“Dengar dulu!” suara Jahan menuntut perhatian. Dia tidak sanggup melihat mereka termakan kata-kata Togok dan yang lain-lain. “Kamu semua dah lupa cerita warga sebelum kita dulu? Dah lupa bencana yang dibawa batu melintang tu? Dah lupa bagaimana warga-warga dulu terkubur di dalam lubuk-lubuk mereka sendiri? Demi mempertahankan lubuk… Demi mempertahankan hak… Tapi tumpas semuanya!”
Sepi. Lubuk kembali sepi.
“Jahan… Batu melintang itu bukan lawan kita! Warga-warga lama dulu tidak berjaya menentangnya. Kita juga tidak akan mampu melawannya. Kita tidak boleh biarkan kaum kerabat yang tinggal kini menjadi korban seperti warga-warga dahulu!”
Pandangan kembali ke arah Jahan. Dagu-dagu yang sejenak tadi disuntik semangat jaguh kembali rapuh. Lubuk kembali sepi. Hanya rumpai yang masih meliang-liuk seolah-olah memomok-momokkan lagi perasaan mereka. Mata-mata belolok kian melayu. Mata-mata yang tajam tinggal terkebil. Timah mengundur ke celah batu. Malong hilang di celah rumpai. Tong dram Jebong sudah tidak berbunyi lagi. Mereka masih ingat cerita-cerita ngeri itu. Mereka masih ingat sejarah hitam yang menghancurkan keindahan Selat Bahagia.
“Lari! Lari!!! Tinggalkan lubuk!!!”
“Ke timur! Ke timur! Semua ikut arah timur!!!”
“Anak-anak aku??? Anak-anak aku masih ada di terumbu!!!”
“Terumbu dah musnah!!! Semuanya dah musnah!!!”
“Anak-anak aku!!!”
“Jangan!!! Kau akan mati nanti!!!”
“Ke timur!!! Ke timur!!!”
“Barat!!! Barat!!!”
“Ayuh!!!!!!!”
Keadaan terlalu genting. Ombak memukul kuat; air melambung tinggi, berkocak terus tanpa henti. Arus kuat menghanyutkan sirip-sirip yang ditumpaskan lelah, hanyut di sisi bangkai-bangkai warga yang terapung-apung dibawa jauh dari tapak musibah.
Hari itu warga lubuk tidak mengenal puak, tidak mengenal kerabat. Setiap suara yang berteriak itu saudara. Setiap sirip yang berkibas di sebelah juga saudara. Setiap anggota warga lubuk saudara juga… baik Jahan, hijau, kuning… semuanya saudara. Hari itu mereka tidak berebut terumbu. Mereka tidak berebut celah batu. Mereka tidak berebut hujung rumpai. Hari itu mereka tidak peduli semua itu. Mereka hanya mahu terus hidup. Mereka hanya mahu melihat esok.
Selat Bahagia diserang dahsyat. Lubuk-lubuk mereka dibedil buku-buku batu. Terumbu-terumbu mereka dihancurkan ceracak-ceracak konkrit. Kaum kerabat Timah banyak yang terkubur di situ. Begitu juga dengan kaum puak Jebong. Bahkan Togok juga turut kehilangan keluarganya. Malong juga. Terlalu banyak yang menjadi mangsa. Ada yang mati di depan mata mereka. Ada yang hilang di balik debu pasir yang terus berapungan.
Warga lubuk hanya mampu melihat buku-buku batu dibedil sebongkah demi sebongkah… hingga rata lubuk mereka… hingga hancur terumbu mereka. Serangan itu berterusan… berpanjangan. Sesekali bedilan itu berhenti buat beberapa ketika. Saat-saat seperti itu ibarat jendela bagi mereka yang berani, mencuri jenguk ke lubuk lama, mencuri lari ke celah terumbu. Mereka cuba mencari warga-warga yang terperangkap. Namun sering saja usaha-usaha itu tidak membuahkan hasil. Bahkan banyak yang turut tumpas dalam usaha-usaha tersebut apabila diserang bedilan-bedilan mengejut yang berlarutan lagi buat satu jangka masa yang panjang. Sepanjang itu jugalah mereka hanya mampu melihat buku-buku batu itu merangkak mencantumkan Tanah Besar dengan Tanah Kecil. Sejak saat itu, tidak siapa yang tahu apa terjadi dengan lubuk di Sekerat Sana.
Mereka yang masih bernyawa di Sekerat Sini amat beruntung kerana datuk nenek mereka sempat melarikan diri; sempat menyelamatkan diri. Sempat menyelamatkan dan menyambung keturunan masing-masing.
“Mereka tidak tahu… atau sengaja tidak mahu ambil tahu… akibatnya beribu nyawa terkorban begitu saja.”
Wajah-wajah yang mulai sugul memberi Jahan semangat baru. Jahan semakin bersemarak mengatur strategi menawan hati, perasaan, kepercayaan dan keyakinan warga lubuknya.
“Mereka mati meninggalkan iktibar yang harus kita kutip dan jadikan panduan bagi anak cucu kita. Kita harus belajar dari keruntuhan semalam. Kita masih ada peluang untuk menyelamatkan warga kita! Kita tidak boleh biarkan keturunan kita terus-terusan menjadi mangsa.”
“Tapi, Jahan…”
Saaaaaaap!!!
Secepat kilat Jahan hilang dari pandangan. Anak gelama yang tiba-tiba muncul entah dari mana memikat hati dan memagut selera. Secepat kilat disambar dan dijulang bagai piala. Timah, Malong, Togok, Jebong dan lain-lain ditinggalkan begitu saja.
“Sandiwara dunia…” sindir Jebong sambil perlahan-lahan kembali ke kubunya.
Yang lain masih terkebil-kebil melihat kerenah Jahan. Dari celah-celah batu, merentasi palang-palang besi, menembusi jeriji-jeriji bakau. Dari muka air, merempuh arus deras, menjunam semula hingga ke usus-usus selat. Sehinggalah akhirnya ditumbangkan lelah.
“Di sini kita mati, di sana pun kita mati,” suara Malong sayup-sayup kedengaran. “Larilah ke mana sekalipun. Kalau dah tiba saatnya, jangan kata batu bongkah, batu ladung pun boleh bawa bencana. Kalau tak mati ditelan, mungkin kail yang menyinggah. Kalau tak dirobek kail, mata jaring yang memunggah.”
Akhirya semangat Jahan sendiri rebah dijajah lesu. Pasrah. Dia melihat pasir. Dia melihat batu. Dia melihat rumpai. Dia melihat sirip-sirip beraneka bentuk dan warna. Dia melihat satu titik noktah saat tubuhnya yang tidak bermaya lagi perlahan-lahan ditarik ke permukaan selat.
TENTANG PENULIS:
 R. Azmann A. Rahman mula menulis sejak di bangku sekolah. Bermula dengan puisi, beliau kemudian meneroka penulisan seni kata apabila bergiat aktif dalam seni dikir barat pada akhir tahun 1980-an. Lagu Di Pinggiran Aidilfitri (1997) dan Aduhai Raja Sehari (lagu tema bagi drama televisyen Kisah Tok Kadi, 2016) adalah antara karya yang pernah dihasilkannya. Cerpen beliau, Maafkan Anan, telah memenangi hadiah kedua dalam Peraduan Menulis Cerpen anjuran bersama Kelab Coretan Remaja Berita Harian dan Restoran A&W pada tahun 1993. Maafkan Anan juga telah dipentaskan oleh Teater Kami pada tahun 1994 dan 2009 dan turut dimuatkan dalam antologi Bingkisan pada tahun 1999. Cerpen-cerpen terbarunya juga akan disertakan dalam antologi cerpen, Tanjong Katong Airnya Biru. Terkini, beliau terlibat sebagai penulis bersama skrip drama Kisah Tok Kadi (2016) dan Kisah Tok Kadi 2 (2017-2018).
R. Azmann A. Rahman mula menulis sejak di bangku sekolah. Bermula dengan puisi, beliau kemudian meneroka penulisan seni kata apabila bergiat aktif dalam seni dikir barat pada akhir tahun 1980-an. Lagu Di Pinggiran Aidilfitri (1997) dan Aduhai Raja Sehari (lagu tema bagi drama televisyen Kisah Tok Kadi, 2016) adalah antara karya yang pernah dihasilkannya. Cerpen beliau, Maafkan Anan, telah memenangi hadiah kedua dalam Peraduan Menulis Cerpen anjuran bersama Kelab Coretan Remaja Berita Harian dan Restoran A&W pada tahun 1993. Maafkan Anan juga telah dipentaskan oleh Teater Kami pada tahun 1994 dan 2009 dan turut dimuatkan dalam antologi Bingkisan pada tahun 1999. Cerpen-cerpen terbarunya juga akan disertakan dalam antologi cerpen, Tanjong Katong Airnya Biru. Terkini, beliau terlibat sebagai penulis bersama skrip drama Kisah Tok Kadi (2016) dan Kisah Tok Kadi 2 (2017-2018).